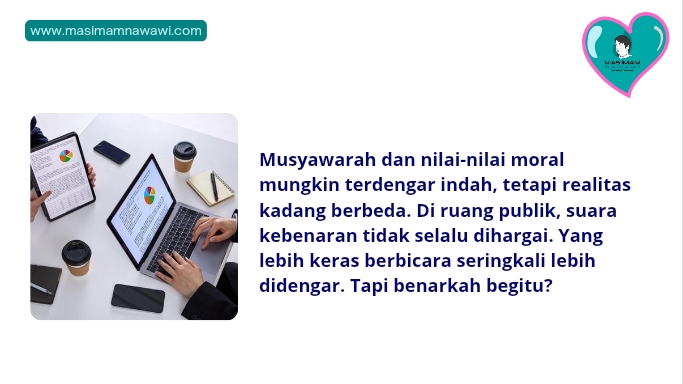Rais ‘Am Hidayatullah, Ust. Abdurrahman Muhammad pernah menegaskan bahwa kunci keberhasilan kepemimpinan adalah musyawarah. Bagi beliau, musyawarah bukan sekadar metode mengambil keputusan. Lebih dari itu, ia adalah benteng pertahanan moral. Dalam musyawarah, setiap suara dihargai dan setiap langkah diputuskan bersama, sehingga kepemimpinan tidak terjebak pada ego atau ambisi pribadi. Orang yang cerdas akan menguatkan benteng itu, bukan sibuk mengemas topeng.
Berbicara soal benteng moral itu saya teringat dengan tulisan Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of The Good Life. Ia memperkenalkan gagasan tentang benteng mental. Menurutnya, kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari status sosial, mobil mewah, rekening bank, atau pujian publik. Semua itu bisa hilang dalam hitungan detik. Jika fondasi kebahagiaan bertumpu pada hal-hal fana, maka hidup akan rapuh.
Artinya benteng mental adalah keyakinan, kedalaman pemikiran dan bagi kita, jelas itu adalah keimanan kepada Allah SWT.
Dalam khazanah Islam, pemikiran serupa hadir dari Buya Hamka. Beliau mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati ada pada diri yang mengenal kebenaran, lalu berani menapaki jalan hidup dengan amar ma’ruf nahi munkar. Seseorang yang merdeka secara batin tidak mudah goyah oleh rayuan dunia. Ia memiliki benteng moral yang menjaganya dari godaan, sekaligus benteng kebahagiaan yang membuat hidupnya bermakna.
Kebutuhan Gen-Z
Pesan ini terasa relevan bagi generasi hari ini, termasuk Gen-Z. Di tengah derasnya arus media sosial, godaan gaya hidup konsumtif, dan tekanan sosial yang kadang menguras energi, kita memerlukan benteng moral sekaligus benteng mental.
Musyawarah, kesadaran akan nilai-nilai kebaikan, dan keberanian untuk memilih kebenaran adalah fondasi penting untuk meraih kebahagiaan yang tidak mudah runtuh.
Tidak perlu rumit, cobalah komunikasi dengan orang tua, bermusyawarahlah dengan mereka. Insya Allah kita akan memperoleh begitu banyak jalan keluar dari masalah yang kita anggap besar dan seperti tak tersolusikan. Jangan lari pada pergaulan yang tidak tepat. Tapi bermusyawarahlah dan beribadahlah dengan baik.
Namun harus kita sadari bahwa upaya membangun benteng semacam itu bukan pekerjaan sekali jadi. Ia butuh latihan, kesabaran, dan keberanian melawan diri sendiri. Namun, ketika benteng itu berdiri kokoh, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati ternyata sederhana: hidup dengan arah, makna, dan ketenangan hati.
Buang Topeng
Hidup pada era sekarang sering menuntut kita untuk mengenakan topeng. Tanpa topeng, banyak orang merasa tersisih dari lingkungannya. Status sosial, gaya hidup mewah, hingga pencitraan dalam media sosial menjadi “senjata” agar tetap tampak ada. Memang melelahkan, tapi sebagian orang percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan dalam dunia yang penuh persaingan dan kefanaan. Dan, inilah akar dari bencana.
Musyawarah dan nilai-nilai moral mungkin terdengar indah, tetapi realitas kadang berbeda. Pada ruang publik, suara kebenaran tidak selalu punya harga. Yang lebih keras berbicara seringkali lebih cepat dapat panggung karena terdengar. Akhirnya, orang memilih aman dengan menyesuaikan diri, bahkan jika itu berarti menyembunyikan keyakinan pribadi. Benteng moral yang kokoh terasa utopis ketika hidup dipenuhi tuntutan pragmatis.
Begitu juga dengan gagasan benteng mental. Rasanya sulit menjaga ketenangan batin jika setiap hari harus terkungkung oleh rasa takut tertinggal, takut miskin, atau takut tidak dapat predikat sukses dari orang lain.
Terlebih lagi mobil mewah dan rekening tebal mungkin memang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi bagi banyak orang, hal-hal itu tetap menjadi simbol kenyamanan dan perlindungan. Akibatnya, tanpa semua itu, hidup terasa rapuh. Dan, sejatinya itulah kerapuhan yang sesungguhnya. Kita tinggal pilih, mau tampak gagah tapi itu topeng. Mau tetap bahagia dan kita punya benteng.*
Mas Imam Nawawi